ZENOSPHERE
science, philosophy, and cultural menagerie
Menyayangi Indonesia
Posted by pada Oktober 16, 2015
A nation is therefore a large-scale solidarity, constituted by the feeling of the sacrifices that one has made in the past and of those that one is prepared to make in the future. It presupposes a past; it is summarized, however, in the present by a tangible fact, namely, consent, the clearly expressed desire to continue a common life.
— Ernest Renan, “What is a Nation?” (1882)
Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pernyataan: saya menyayangi bangsa Indonesia.
Tentu saja cetak tebalnya harus diperhatikan. Hal itu sangat penting, dan akan kita uraikan sambil berjalan.
Sebagian pembaca mungkin ingat, beberapa tahun lalu, saya pernah menulis bahwa Indonesia adalah negara yang batas-batasnya ambigu. Genetiknya campuraduk: ada Melayu, Jawa, Bugis; lalu dibumbui keturunan Arab, Tionghoa; ada juga dari Eropa seperti Belanda dan Portugis. Bahasa daerahnya ribuan. Adat dan kulinernya juga. Lebih jauh lagi adalah soal agama: ada lima dan semuanya hasil impor. Islam dari Arab, Katolik/Protestan dari Eropa, kemudian Hindu dan Buddha dari India.
Dapat dibilang bahwa Indonesia itu semacam “Republik Gado-gado”. Alih-alih mempunyai ciri yang dominan, justru di negeri ini identitasnya berwarna-warni.
Otomatis timbul pertanyaan: bangsa Indonesia itu apa? Di mana identitasnya? Bagaimana mungkin silang-sengkarut seperti itu bisa dilabeli menjadi “bangsa” dan “negara”.
Jawabannya, menurut saya, terdapat dalam esai Ernest Renan yang dikutip di awal tulisan. Dalam What is a Nation? Renan menyebut ada dua alasan sekelompok orang bisa disebut sebagai bangsa: (1) warisan sejarah yang membentuk rasa senasib-sepenanggungan, dan (2) persetujuan untuk hidup bersama.
Hal itu juga berlaku untuk bangsa Indonesia. Ratusan tahun dijajah oleh Belanda, warga berbagai daerah merasa memiliki kesamaan. Berangkat dari situlah muncul niat persatuan seperti Sumpah Pemuda (“berbangsa satu, bangsa Indonesia”). Meskipun begitu saya ingin fokus pada poin yang nomor 2.
Martin Buber: Antara Aku, Kau, dan Dia
Posted by pada Oktober 1, 2015
Bapak Martin Buber, teolog dan filsuf asal Austria, adalah sosok pemikir yang unik. Dalam hidupnya dia menyerap banyak ide, baik dari pemikir religius maupun ateis, sebagai contoh Kierkegaard, Nietzsche, dan Feuerbach. Dia juga suka mempelajari agama Asia seperti Hindu dan Taoisme. Dapat dibilang bahwa beliau pemikir yang berwawasan luas.
Martin Buber (1878-1965)
(image credit: Wikimedia Commons)
Ditinjau dari ide-idenya, Buber sering dikelompokkan sebagai filsuf eksistensialis. Dia berkutat dengan pertanyaan berikut: bagaimana manusia dapat hidup dengan bermakna di zaman modern?
Tema itu didorong oleh pengalaman Buber menyaksikan industrialisasi di Eropa, yang disusul pecahnya Perang Dunia I dan II. Di satu sisi modernitas membawa banyak kebaikan, termasuk di antaranya ilmu kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Akan tetapi di sisi lain kemajuan itu datang dengan harga mahal. Alih-alih makmur dan bahagia, justru masyarakat porak-poranda dan dilanda kegalauan eksistensial.
Namun biarpun seorang teolog, Buber tidak lantas bicara akhirat dan agama. Kita ini hidup di dunia, demikian kata Buber. Oleh karena itu jawaban masalah-masalah kita juga harus dicari di dunia.
I possess nothing but the everyday out of which I am never taken. The mystery is no longer disclosed, it has escaped or it has made its dwelling here where everything happens as it happens. I know no fulness but each mortal hour’s fulness of claim and responsibility.
(Martin Buber, “Dialogue”, terj. Ronald Gregor-Smith)
Nah, berangkat dari situlah Buber merumuskan gagasan filsafat. Secara unik idenya bersandar pada tiga kata yang familiar, yaitu Aku (“I”), Kau (“You”), dan Dia (“It”).*
- *) Buber aslinya menulis dalam Bahasa Jerman. Penerjemahan di atas mengikuti versi Inggris oleh Walter Kaufmann (1970)
Xenophanes: Pemikir Bebas dari Colophon
Posted by pada Juni 16, 2015
Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, peradaban Yunani Kuno mulai menggeliat di bidang ilmu. Di berbagai wilayahnya muncul tokoh-tokoh yang menyebarkan gagasan. Dimulai oleh Thales di kota Miletus, kemudian muncul Pythagoras dari Samos, Alcmaeon dari Croton, serta Heraclitus dari Ephesus. Detail ajaran mereka bervariasi, namun semangat intinya sama: mencoba memahami dunia lewat rasio.
Dari yang tadinya takhayulan, mempercayai ramalan dan dewa-dewi, menjadi lebih kritis dan logis. Mereka juga memperkenalkan cara berpikir naturalistik: bahwa alam semesta bersifat teratur dan mengikuti hukum sebab-akibat. Oleh karena itu, wajar jika Yunani abad ke-6 SM dipandang sebagai tempat lahirnya ilmu filsafat.
Nah, termasuk di antara tokoh yang mendorong perubahan tersebut adalah Xenophanes dari Colophon. Dia terkenal sebagai pengkritik agama Yunani Kuno, yakni penyembahan dewa-dewi di Gunung Olympus.
Xenophanes dari Colophon (c. 570-475 SM)
(image credit: Wikimedia Commons)
Bagi kita di zaman modern, agak susah membayangkan bahwa — di satu masa — pernah ada yang menyembah Zeus dan kawan-kawan. Seolah-olah mereka hanya tokoh dunia mitologi. Pun demikian, faktanya memang mereka dulu disembah. Penggalian arkeologi menemukan reruntuhan kuil dan altar di berbagai kota. Menyebut dua di antaranya: Kuil Artemis di Ephesus serta Kuil Apollo di Delphi.
Di lingkungan seperti itulah Xenophanes hidup dan berkarir. Sebagaimana telah disebut, dia menolak politeisme, meskipun begitu yang menarik adalah argumennya. Dapat dibilang merupakan versi awal gagasan yang terkenal di zaman modern, yaitu skeptisisme dan relativisme.
Seperti apa detailnya akan segera kita lihat. Meskipun begitu, sebelum lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan sosok pemikirnya.
Peta Bintang Al-Sufi
Posted by pada Mei 31, 2015
Dalam posting beberapa waktu lalu, kita membahas tentang transmisi pengetahuan Yunani-Romawi ke peradaban Islam Abbasiyah. Melalui serangkaian peristiwa yang kompleks, termasuk diantaranya geopolitik, berbagai manuskrip karya Euclid, Galen, dan Ptolemaeus dapat masuk ke tanah Arab. Berbagai manuskrip ini kemudian diterjemahkan dan dipelajari, sedemikian hingga akhirnya dunia sains Muslim maju pesat.
To be clear, yang berperan di situ bukan hanya Yunani-Romawi. Ada juga sumbangsih matematika dari India, plus filsafat Persia. Akan tetapi soal mereka tidak kita bahas di sini.
Sebagaimana Isaac Newton pernah menyebut, “berdiri di atas bahu raksasa”, demikian pula dengan sains Islam Abbasiyah. Kemajuan mereka sedikit-banyak ditunjang masukan ilmu bangsa lain. (Selanjutnya bisa dibaca dalam posting yang di-link)
Nah, termasuk bidang ilmu yang mendapat pengaruh luar itu adalah astronomi. Sekitar abad ke-9 Masehi, banyak astronom Muslim membaca buku Almagest karya Ptolemaeus. Ptolemaeus dalam karyanya menggolongkan 48 rasi bintang yang terlihat dari Yunani. Berbagai rasi itu kemudian diadaptasi astronom Muslim, diberi nama Arab, dan ditambahi hasil pengamatan baru.
Sebagai contoh, rasi Aquila (Elang) diberi nama Uqab; bintang paling terangnya disebut Al-Nasr Al-Tair (sekarang jadi Altair). Cassiopeia menjadi dzat-al-kursi (“perempuan duduk”) mengikuti ilustrasi. Sementara itu Orion menjadi al-Jabbar — dalam bahasa Indonesia berarti raksasa.
Bisa ditebak, silang-ilmu lintas-budaya itu kemudian tercermin dalam peninggalan arkeologi. Salah satunya peta bintang yang akan kita bahas, berjudul Kitab Suwar al-Kawakib al-Tsabitah, buatan astronom Persia Abdul Rahman Al-Sufi. Karya ini mempunyai keunikan: menampilkan rasi bintang Yunani, tetapi dengan ilustrasi dan dekorasi Islam.
Yes, you heard that right. Percampuran budaya Yunani dan Islam! 😀 Soal ini akan dibahas lebih detail di bawah.
Zaman internet begini, kita beruntung, sebab banyak museum membuka konten mereka secara online. Demikian pula peta bintang Al-Sufi — bisa dibaca di BNF Gallica. Meskipun begitu kalau pembaca punya program Stellarium bisa langsung melihatnya. Cukup set starlore ke versi Arabic. Hasilnya akan tampak seperti berikut.
Peta Bintang Al-Sufi di Stellarium. Ada Centaurus pakai sorban!!
(klik untuk memperbesar)
Nah, sekarang kita akan mulai membahas isi bukunya. Kitab Suwar al-Kawakib al-Tsabitah dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Book of Fixed Stars.
Satu hal yang mencolok adalah teknik Al-Sufi menjelaskan legenda Yunani yang tidak ada versi Islamnya. Misalnya rasi Perseus. Alih-alih bercerita tentang pahlawan yang mengalahkan Medusa, Al-Sufi mendeskripsikan sebagai “Hamil Ra’s Al-Ghul” — pembawa kepala setan.
Menyingkap Wajah Saturnus (1610-1660)
Posted by pada Mei 23, 2015
Siapa yang tidak tahu planet Saturnus? Dibandingkan dengan tetangganya di tata surya, planet yang satu ini sangat unik, sebab punya cincin besar yang mengitarinya.
Bisa dilihat dalam foto di bawah, cincin pengiring Saturnus mempunyai pola belang-belang yang teratur. Sepintas lalu planet ini tampak unik dan artistik.
(image credit: NASA JPL Photojournal)
Menariknya, biarpun sekarang populer, planet Saturnus dulunya kontroversial. Butuh waktu puluhan tahun sejak pertama kali diamati lewat teleskop, di tahun 1610, hingga para ahli memahami bentuknya yang unik.
Minimnya kualitas teleskop generasi awal, ditambah perilaku Saturnus yang ‘ajaib’, membuat astronom di seluruh Eropa kebingungan. Planet yang satu ini bentuknya terus berubah. Kadang bulat, kadang lonjong, namun yang paling misterius: kadang-kadang memunculkan telinga! Tidak kurang tokoh besar seperti Galileo, Johannes Hevelius, sampai Christiaan Huygens dibuat penasaran.
Tentunya zaman sekarang kita sudah punya teleskop canggih, bahkan bisa mengirim wahana angkasa ke planetnya. Namun berbeda dengan zaman dulu.
Suatu hari di bulan Juli 1610, Galileo Galilei mengarahkan teleskop untuk meneliti Saturnus, dan melihat penampakan mengejutkan.
Penakluk yang Kurang Berbudaya
Posted by pada April 25, 2015
Peradaban Romawi adalah pemain kunci dalam sejarah. Mengenai hal ini semua orang sudah tahu. Bahkan di Indonesia, yang relatif tidak berhubungan, nama Romawi sedikit-banyak disinggung di pelajaran sekolah.
Romawi dengan angkatan perangnya berkuasa di Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Adapun rentang terjauh dicapai oleh pemimpinnya, Kaisar Trajan, di tahun 117 Masehi. Dari Semenanjung Iberia di Spanyol sampai Laut Kaspia di Asia Tengah; dari Inggris di utara sampai Mesir di selatan. Dapat dibilang bahwa mereka kekuatan adidaya zaman kuno.
Puncak kekuasaan Romawi di bawah Trajan (117 M)
(image credit: Tataryn77 @ Wikimedia Commons)
Adapun di zaman modern, banyak warisan Romawi mewarnai kehidupan kita. Mulai dari huruf Latin, sistem legislatif, profesi pengacara, sampai bentuk jembatan lengkung termasuk di dalamnya. Bukan berarti semua murni Romawi, sih. Sebagian diadaptasi dari peradaban terdahulu; sebagian mereka temukan sendiri. Meskipun begitu intinya tetap: banyak elemen kehidupan mereka terhantar sampai ke kita.
Ironisnya, biarpun sukses sebagai penguasa, Romawi bukannya tanpa kekurangan. Salah satunya masalah budaya. Di bidang ini Romawi berhutang pada bangsa yang mereka taklukkan, yaitu Yunani Kuno.
Masa Kejayaan dengan Banyak Pengaruh
Posted by pada April 4, 2015
Beberapa waktu sekali, jika sedang ngobrol dengan teman yang Muslim konservatif, muncul topik tentang “masa keemasan Islam”. Bukan berarti mereka radikal, sih — orangnya moderat saja, namun karena satu dan lain hal merasa punya identitas keagamaan yang kuat. Jadinya suka berkaca dan membandingkan dengan masa lalu.
Permasalahannya tentu, apakah klaim “masa keemasan” itu valid atau tidak? Nah ini yang perlu ditelusuri. Periode yang dimaksud adalah sekitar abad ke-9 hingga 12 Masehi, di mana kekuasaan Khilafah Abbasiyah mencapai puncaknya, dan menghasilkan kemajuan sains, teknologi, dan budaya.
Kaum Muslim yang religius, apalagi yang jarang baca sejarah, biasanya gampang terpancing klaim di atas. Seolah-olah semua kejayaan itu berasal murni dari Islam; tidak ada sumbangan kebudayaan lain. Kenyataan sebenarnya agak lebih rumit. Sebagaimana pernah diuraikan dalam posting tentang alkimia zaman dulu: warisan ilmiah Islam merupakan campur-baur Yunani, Romawi, India, dan Persia.
Oleh karena itu, sebagai orang yang kebetulan cukup sering baca tentang sejarah ilmu, ada baiknya kalau saya berbagi sedikit lewat posting ini. Di satu sisi, betul bahwa Islam Abbasiyah mempunyai kemajuan ilmiah yang mumpuni. Namun di sisi lain kemajuan itu dibangun oleh kontribusi lintas bangsa dan budaya.
Fun with Math: Menggelinding tapi Tidak Bulat
Posted by pada Februari 4, 2015
Di dunia sehari-hari, kita sering melihat benda bulat, sebagai contoh roda dan bola sepak. Benda bulat mempunyai keunikan: apabila didorong dia tidak cuma bergeser, melainkan juga berputar. Secara umum geraknya disebut “menggelinding”.
Nah, tapi ada yang menarik.
Biarpun gerak menggelinding sering diasosiasikan dengan lingkaran, ternyata ada juga bentuk lain yang bisa melakukannya. Namanya segitiga Reuleaux — animasinya bisa dilihat di bawah.
(GIF diadaptasi dari: Youtube / Jill Britton)
Sebuah ban yang berbentuk segitiga! Luar biasa bukan? 😀 Sebagaimana bisa dilihat pergerakannya mirip dengan ban biasa, cuma bentuknya yang berbeda.
Nah, ditinjau secara matematika, segitiga Reuleaux di atas termasuk dalam keluarga “bangun berlebar konstan”, atau dalam bahasa Inggrisnya curves of constant width. Bangun jenis ini mempunyai keistimewaan: diputar bagaimanapun diameternya tidak berubah. Makanya dapat menggelinding dengan stabil. Jika kita tumpangkan papan, seperti dalam animasi, maka takkan bergoyang-goyang naik dan turun.
Contoh-contoh bangunnya bisa dilihat sebagai berikut.
(image credit: Wikimedia Commons)
Tentunya sampai di sini timbul pertanyaan. Telah disebut bahwa bangun-bangun di atas mempunyai diameter yang tetap. Akan tetapi mereka bukan lingkaran. Jika bukan lingkaran… mengapa diameternya bisa tetap?
Melestarikan Kenangan
Posted by pada Januari 31, 2015
Dalam literatur mitologi Yunani-Romawi, terdapat sebuah epik yang berjudul Aeneid. Epik ini berkisah tentang Aeneas, bekas prajurit Troya yang memimpin rakyatnya mencari tempat tinggal baru setelah kota mereka dihancurkan. Selama bertahun-tahun mereka berlayar dan mengembara, menjalani berbagai petualangan, sebelum akhirnya mendarat di tanah Latium (sekitar Italia modern).
Ada sebuah episode yang memorable di dalamnya, ketika Aeneas sedang berjalan-jalan di sebuah kota dan merasakan deja vu. Dia melihat kemiripan dengan kampung halaman yang telah lama ditinggalkan:
Proceeding on, another Troy I see,
Or, in less compass, Troy’s epitome.
A riv’let by the name of Xanthus ran,
And I embrace the Scæan gate again.(Virgil, “Aeneid” Book III, terj. John Dryden)
Kota itu dibangun oleh pengungsi Troya yang lain — yang Aeneas tidak tahu juga selamat.
Syahdan, ketika kota Troya digasak Yunani, seluruh warga di dalamnya dibunuh atau dijadikan budak. Termasuk di dalamnya adalah Andromache, istri Pangeran Hector yang gugur dalam perang. Biarpun berstatus ningrat namun ia tak dianggap; dijadikan budak oleh Neoptolemus.
Pemuda Sederhana Naik Tahta
Posted by pada Januari 21, 2015
Pada tahun 161 Masehi, Imperium Romawi tengah berjaya di seantero Eropa, membujur dan melintang berpusat di Italia. Batas baratnya Semenanjung Iberia, yang di masa kini wilayah Spanyol dan Portugis. Di ujung timurnya Jazirah Arab dengan kota besar Palmyra dan Antioch, berbatasan dengan Persia. Dengan armada kapalnya mereka menyeberang laut, sedemikian hingga setelah berabad-abad, Inggris yang dingin hingga Mesir yang terik ikut jatuh ke tangan mereka.
Imperium Romawi — bisa ditebak — adalah bangsa penakluk tanpa ampun. Di laut mereka jaya, dan di darat mereka menggila. Bahkan seluruh Laut Mediterania mereka lingkupi. Dari pantai Gibraltar ke Italia, hingga Balkan dan Asia, juga sisi seberangnya di Afrika Utara: semua milik Romawi.
Mare Nostrum, begitu bangsa Romawi menyebut Laut Mediterania. Dalam bahasa Latin berarti “Laut Kami”. Zaman dulu banyak peradaban kuno menyisirinya, namun sekarang semua milik Kaisar.
Peta wilayah Romawi sekitar tahun 161 M
(adapted from: Wikimedia Commons)
Dengan konteks seperti itu, wajar jika dalam sejarah banyak orang ingin jadi Kaisar, bahkan jika perlu saling membunuh. Meskipun begitu selalu ada pengecualian.
Ketika Marcus Aurelius naik tahta, dia melakukan terobosan radikal: menunjuk saudara angkatnya, Lucius Verus, sebagai Kaisar Pendamping. Untuk pertama kalinya Imperium Romawi dipimpin oleh “Kaisar Kembar” — di mana yang satu berdiri setara dengan yang lain.
Secara resmi Marcus mengambil nama gelar “Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus”, sementara Lucius “Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus”.
Dua Kaisar Romawi: Marcus Aurelius (kiri) dan Lucius Verus (kanan)
Untuk dicatat, dalam sejarah Romawi terdapat beberapa Kaisar yang menunjuk dua pewaris untuk naik tahta bersama, tapi tidak pernah terwujud. Meskipun begitu yang dilakukan Marcus tetap spesial, sebab dia sendiri yang membagi tahta miliknya.
Peristiwa ini jelas mengejutkan. Alih-alih merengkuh tahta seperti umumnya para raja, Marcus justru enggan dan berbagi. Pertanyaannya adalah, mengapa?
![[img] Martin Buber (1878-1965)](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/10/martin_buber_portrait.jpg?w=250)
![[img] Xenophanes engraving](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/06/xenophanes_in_thomas_stanley_history_of_philosophy.jpg?w=300)
![[img] Stellarium Arabic sky culture](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/05/stellarium-arab-skyculture.jpg?w=500)
![[img] Planet Saturnus](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/05/saturn-pia11141-resized.jpg?w=450)
![[img] Imperium Romawi di tahun 117 M](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/04/roman_empire_trajan_117ad.png?w=450)
![[gif] segitiga reuleaux](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/02/reuwheel.gif?w=630)
![[img] poligon reuleaux](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/02/reuleaux_polygons_wikicommons.png?w=300)
![[img] Roman Map around time of Antoninus](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/01/roman-map-antoninus-adapted-from-wikicommons1.jpg?w=500)
![[img] Marcus Aurelius & Lucius Verus](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/01/marcus-and-lucius1.jpg?w=400)
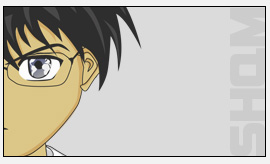


Recent Comments