ZENOSPHERE
science, philosophy, and cultural menagerie
Monthly Archives: Oktober 2015
Menyayangi Indonesia
Posted by pada Oktober 16, 2015
A nation is therefore a large-scale solidarity, constituted by the feeling of the sacrifices that one has made in the past and of those that one is prepared to make in the future. It presupposes a past; it is summarized, however, in the present by a tangible fact, namely, consent, the clearly expressed desire to continue a common life.
— Ernest Renan, “What is a Nation?” (1882)
Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pernyataan: saya menyayangi bangsa Indonesia.
Tentu saja cetak tebalnya harus diperhatikan. Hal itu sangat penting, dan akan kita uraikan sambil berjalan.
Sebagian pembaca mungkin ingat, beberapa tahun lalu, saya pernah menulis bahwa Indonesia adalah negara yang batas-batasnya ambigu. Genetiknya campuraduk: ada Melayu, Jawa, Bugis; lalu dibumbui keturunan Arab, Tionghoa; ada juga dari Eropa seperti Belanda dan Portugis. Bahasa daerahnya ribuan. Adat dan kulinernya juga. Lebih jauh lagi adalah soal agama: ada lima dan semuanya hasil impor. Islam dari Arab, Katolik/Protestan dari Eropa, kemudian Hindu dan Buddha dari India.
Dapat dibilang bahwa Indonesia itu semacam “Republik Gado-gado”. Alih-alih mempunyai ciri yang dominan, justru di negeri ini identitasnya berwarna-warni.
Otomatis timbul pertanyaan: bangsa Indonesia itu apa? Di mana identitasnya? Bagaimana mungkin silang-sengkarut seperti itu bisa dilabeli menjadi “bangsa” dan “negara”.
Jawabannya, menurut saya, terdapat dalam esai Ernest Renan yang dikutip di awal tulisan. Dalam What is a Nation? Renan menyebut ada dua alasan sekelompok orang bisa disebut sebagai bangsa: (1) warisan sejarah yang membentuk rasa senasib-sepenanggungan, dan (2) persetujuan untuk hidup bersama.
Hal itu juga berlaku untuk bangsa Indonesia. Ratusan tahun dijajah oleh Belanda, warga berbagai daerah merasa memiliki kesamaan. Berangkat dari situlah muncul niat persatuan seperti Sumpah Pemuda (“berbangsa satu, bangsa Indonesia”). Meskipun begitu saya ingin fokus pada poin yang nomor 2.
Martin Buber: Antara Aku, Kau, dan Dia
Posted by pada Oktober 1, 2015
Bapak Martin Buber, teolog dan filsuf asal Austria, adalah sosok pemikir yang unik. Dalam hidupnya dia menyerap banyak ide, baik dari pemikir religius maupun ateis, sebagai contoh Kierkegaard, Nietzsche, dan Feuerbach. Dia juga suka mempelajari agama Asia seperti Hindu dan Taoisme. Dapat dibilang bahwa beliau pemikir yang berwawasan luas.
Martin Buber (1878-1965)
(image credit: Wikimedia Commons)
Ditinjau dari ide-idenya, Buber sering dikelompokkan sebagai filsuf eksistensialis. Dia berkutat dengan pertanyaan berikut: bagaimana manusia dapat hidup dengan bermakna di zaman modern?
Tema itu didorong oleh pengalaman Buber menyaksikan industrialisasi di Eropa, yang disusul pecahnya Perang Dunia I dan II. Di satu sisi modernitas membawa banyak kebaikan, termasuk di antaranya ilmu kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Akan tetapi di sisi lain kemajuan itu datang dengan harga mahal. Alih-alih makmur dan bahagia, justru masyarakat porak-poranda dan dilanda kegalauan eksistensial.
Namun biarpun seorang teolog, Buber tidak lantas bicara akhirat dan agama. Kita ini hidup di dunia, demikian kata Buber. Oleh karena itu jawaban masalah-masalah kita juga harus dicari di dunia.
I possess nothing but the everyday out of which I am never taken. The mystery is no longer disclosed, it has escaped or it has made its dwelling here where everything happens as it happens. I know no fulness but each mortal hour’s fulness of claim and responsibility.
(Martin Buber, “Dialogue”, terj. Ronald Gregor-Smith)
Nah, berangkat dari situlah Buber merumuskan gagasan filsafat. Secara unik idenya bersandar pada tiga kata yang familiar, yaitu Aku (“I”), Kau (“You”), dan Dia (“It”).*
- *) Buber aslinya menulis dalam Bahasa Jerman. Penerjemahan di atas mengikuti versi Inggris oleh Walter Kaufmann (1970)
![[img] Martin Buber (1878-1965)](https://zenosphere.files.wordpress.com/2015/10/martin_buber_portrait.jpg?w=250)
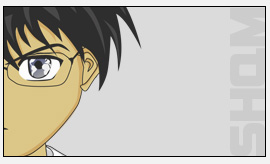


Recent Comments